Oleh: Ignatius Haryanto
ANDA pernah menebar remah-remah atau makanan ikan di depan sebuah kolam atau akuarium? Anda tentu sangat familiar dengan situasi ikan berkelompok-kelompok berebut makanan, dan harap-harap cemas menanti lemparan berikutnya. Apa yang anda rasakan pada saat melihat ikan-ikan menunggu tersebut? Anda mungkin tersenyum, dan ingin sedikit bermain-main dengan remah-remah makanan itu.
Entah mengapa, namun asosiasi itulah yang saya temukan ketika melihat pelbagai acara reality show di sejumlah televisi kita (daftar reality show ini bisa melihat pada Budi Suwarna, Kompas 18 Januari 2009, dan Kompas 24 Mei 2009), terutama adalah reality show yang mengambil fokus pada orang-orang marjinal. Banyak acara reality show yang menampilkan sosok orang marjinal , namun dari perspektif saya, orang-orang marjinal lebih jadi komodifikasi ketimbang diangkat harkat martabatnya dalam acara seperti ini
Playing God?
Ambillah satu tayangan yang bernama “Paket Misterius” dimana, ada seseorang misterius di suatu siang biasa-biasa mengetuk pintu sebuah rumah sederhana dan menyerahkan paket terbungkus rapi. Si pemilik membuka paket dan menemukan uang tunai dalam jumlah besar. Namun si pemberi paket dalam hati menyimpan agenda: kalau si penerima paket menikmati uang itu sendiri, ia dianggap gagal. Uang akan diambil kembali, dengan dalih salah alamat. Jika si penerima paket membagikan uang itu kepada orang lain, maka ia lulus ujian, ia akan dapat paket lainnya.
Dalam hati saya berpikir, kamu ini siapa? Tuhan atau siapa, mempermainkan anugrah atau takdir hidup seseorang dengan modal jutaan rupiah untuk diberikan dan diambil seturut criteria yang dibuatnya itu?
Kalaupun seseorang menikmati uang yang dianggapnya sebagai anugrah, apakah salah jika ia menikmatinya sendirian? Dan mengapa yang satu ini dianggap lebih rendah, atau ‘salah’ sehingga boleh ditarik kembali, dan diberikan kepada korban eksperimen berikutnya? Apakah ini bukan suatu penghinaan luar biasa dalam bentuk permainan perasaan, permainan soal anugrah, atau dalam bahasa lainnya, “Are you playing God now?”
Bagaimana pula hati kita bereaksi ketika melihat seorang ibu dalam tayangan “Uang Kaget”, yang tergopoh diberi uang tunai jutaan rupiah dan harus dihabiskan dalam waktu 30 menit. Usai bersyukur dan berucap terima kasih, ibu ini kelabakan untuk mencari tempat dimana ia bisa menghabiskan uang ini. Ia berlari kesana kemari untuk membeli kulkas, sepeda, kompor gas, televisi, emas, dan lain-lain (astaga, kenapa semua adalah barang konsumtif? Kenapa tak terpikir, masukkan saja ke tabungan, dan setiap saat bisa dipergunakan jika diperlukan?)
Belum lagi tayangan “Dibayar Lunas” yang sungguh-sungguh menipu dan menakut-nakuti orang kecil yang punya hutang (kamera bahkan sampai menyorot dimana si ibu atau bapak itu menaruh uang simpanannya di dalam rumah), menuntut pembayaran seluruh hutang segera (saya heran darimana mereka tahu mereka berhutang dan berapa jumlahnya?), bahkan menuntut seluruh harta yang dimiliki untuk diserahkan, sebelum kemudian wajah-wajah ganas berubah – pura-pura – jadi welas asih. Hutang dibayarkan, sembari diberi pesan “jangan berhutang lagi…” (jadi siapa yang sesungguhnya tak mengerti realitas orang kecil?)
Selintas memang kedengaran reality show seperti ini telah bertindak mulia, membagikan uang kepada orang-orang kecil, tetapi di luar itu, para penonton diajak jadi pengintip dari “culture shock”-nya orang-orang kecil mendapatkan rejeki yang tak dibayangkan sebelumnya.
Rasanya reality show macam begini telah menghina orang miskin, kemiskinan itu sendiri, dan mempermainkan kondisi kemiskinan serta kekayaan hanya dalam hitungan menit. Luar biasa bukan?
Kekuasaan Kamera
Annette Hill (dalam bukunya Reality TV: Audiences and Popular Factual Television, 2005) menyebut bahwa Reality Show adalah program hiburan yang melibatkan orang-orang biasa. Genre reality show ini ada pada dua perbatasan; perbatasan antara informasi dan entertainment (seperti infotainment), dan juga perbatasan antara film documenter dan drama. Pada awal abad 21 ini, genre demikian memang berkontribusi besar untuk pemasukan banyak studio-studio besar TV dunia, dan juga di Indonesia.
Namun kritikus media di berbagai tempat pun sudah banyak melontarkan pandangan mereka atas program-program seperti ini, yang disebutnya sebagai: menjadikan penonton tak ubah seperti tukang ngintip, murahan, program sensasional. Michael Tracey dari Universitas Colorado, sebagaimana dikutip Hill, menyebutkan program reality show itu jadi terkenal karena programnya bodoh dan membodohi penonton.
Belum lagi jika kita bicara soal privacy yang harus dilindungi. Banyak dari mereka yang jadi aktor, atau tampil di acara reality show, mungkin tak sadar dengan soal privacy yang harusnya mereka lindungi, dan mereka seolah takluk di bawah sorotan kamera, karena mungkin kamera dalam bayangan mereka mewakili suatu kepentingan yang jauh lebih tinggi dari dirinya, atau ia mewakili suatu ‘kebenaran’ dimana ia mungkin terlibat atau tidak terlibat dalam proses pembentukannya. Kamera seolah menjadi si ‘tuan’ yang harus dipahami, dituruti, dan dibiarkan leluasa mengambil gambar apapun, dalam angle apapun, untuk menghadirkan situasi yang sangat melodramatik. Jarang ada yang protes ketika tahu-tahu – tanpa sepengetahuan orang itu sebelumnya – menyorot muka mereka, menyorot tingkah laku mereka, dan mereka terpaksa harus berakting di depannya.
Kembali lagi, ini adalah bisnis pertunjukan, bukan bakti sosial, atau acara charity dimana ketika uang telah diberikan, pemberinya tak lagi berpikir apa yang akan digunakan oleh si penerima. Tapi dalam konteks bisnis pertunjukan, uang yang demikian besar telah menghasilkan gegar budaya bagi si miskin, dan memperhatikan gegar budaya itu asyik. Kita bisa tertawa sepuasnya… begitu logika para pembuat reality show seperti ini.
Uang sekian juta atau sekian belas juta yang telah dikeluarkan toh akan terkompensasi dengan iklan yang akan muncul per 10 menit tayangan. Jadi uang tadi bukan sesembahan gratis, tapi tak lebih merupakan bagian dari ongkos produksi tayangan saja. Uang bisa diganti dengan baju, dengan rumah baru (tayangan “Bedah Rumah” misalnya), atau apapun yang dianggap pas.
“Tukar Nasib” juga sejenis bermain-main dalam level yang lain. Orang diajak bertukar nasib dan kita akan melihat kecanggungan dari peran-peran saling silang tersebut. Ibu notaris disuruh jadi pengasap ikan asin. Anaknya yang terbiasa memanggil pembantu untuk semua urusan, kini sibuk menahan muntah untuk bau tak sedap di sekitarnya.
Walau cuma ‘main’ selama tiga hari, tapi keseluruhan gegar budaya dari dua sisi disorot. Kecanggungan direktur perusahaan jadi tukang pancing, dan sebaliknya ibu yang biasa mengasap ikan kini harus duduk seharian di kantor dingin ber-AC, dengan tumpukan dokumen yang ia tak mengerti satu lembar pun. Ia mendadak jadi buta huruf, ia mendadak jadi lumpuh, tak tahu apa yang harus diperbuat.
Sekali lagi, acara-acara ini adalah bagian dari program hiburan. Bukan tayangan serius yang merepresentasikan realitas hidup orang-orang kecil yang butuh empati atau pertolongan. Jadi ini bukan program realitas betulan, tapi program acara hiburan yang seolah-olah seperti betulan.
Acara seperti ini tak perlu dilarang, tetapi para penonton harus lebih cerdas dan cerdik memilih tayangan untuk dikonsumsi dan tak menjadikan tayangan seperti ini jadi wakil dari kebenaran, serta tak membuat sejumlah penonton jadi bermimpi baru: “Kapan giliran saya dapat uang jutaan rupiah dalam 30 menit.
Sumber: Remotivi
•••
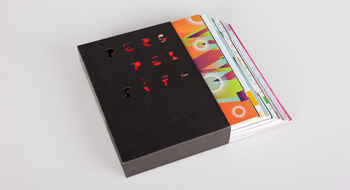



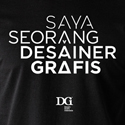



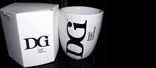

 1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto
1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong
2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan
3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com
www.underconsideration.com
