Oleh FX Harsono
Saya agak terkejut membaca tulisan Saudara Eka Sofyan Rizal yang berjudul “Desain Itu Seni Terapan”. Pernyataan tentang terapan sudah jelas bahwa itu melekat dengan fungsi, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi ketika kata terapan dikonotasikan sebagai sebuah hasil kerja dari seorang desainer yang harus obyektif dan bebas dari pengaruh subyektifitas, hal ini yang agak membingungkan. Yang saya tangkap bahwa Eka terjebak pada pemikiran yang dilandasi oleh ideologi modernisme. Yang mana antara seni terap dan seni murni dilihat dalam konteks oposisi biner. Seniman pembuat karya seni murni dan desainer pembuat karya seni terap. Seniman dalam penciptaan karya seni otonom, karya seni murni merupakan ekspresi individu yang subyektif yang menghadirkan keunikan individu, karya yang memancarkan otentisitas seniman yang bersifat tunggal, deepness dan aura estetis yang subyektif dan individual sangat mewarnai karya seni.
Pemikiran yang dilandasi oleh modernisme ini sudah lama ditinggalkan oleh para seniman di dunia sejak tahun tahun 60-an hingga 70-an. Di Indonesia sendiri pemikiran ini selesai sejak munculnya Gerakan Seni Rupa Baru. Praktik seni rupa sulit sekali dibedakan dengan praktik pembuatan karya seni terap. Seni murni yang tadinya dikerjakan oleh tangan seniman sendiri, karena tangan seniman dianggap sebagai jarum seismograf dari rasa dan emosi seniman sudah ditinggalkan. Pemujaan terhadap otentisitas dan ketunggalan tidak lagi menarik. Karya-karya seni rupa meninggalkan deepness kini menghadirkan hal-hal yang banal, kitsch, dan sangat sementara – seperti karya-karya instalasi. Seniman membuat perencanaan yang dikerjakan oleh sebuah team pelaksana sebagaimana seorang desianer.
Sebaliknya karya seorang desainer tidak lagi hanya sekedar bermuara pada obyektifitas dan pasar. Saya melihat bahwa karya-karya desianer grafis yang baik serta memiliki keunikan dan sangat cerdas, tidak bisa dipungkiri bahwa itu bersumber pada pengalaman individu, pemahaman kebudayaan yang juga bersifat personal serta pengalaman hidup dan lainnya yang sangat personal. Jelas bahwa subyektifitas melekat pada setiap karya seni yang bernama desain.
Praktik dalam dunia desain grafis seringkali sulit dibedakan dengan praktik seni rupa lainnya. Sebagai contoh karya “Change Yourself” dari Iwang harus dikategorikan apa? Seni rupa? Atau Desain Grafis? Karya itu secara kebentukan dan media-media yang digunakan adalah sebagai desain grafis, tetapi karya itu tidak hanya beredar dan dimaknai sebagai desain grafis, karena karya itu telah dipamerkan di galeri seni rupa kontemporer sebagai proyek seni rupa yang bagus. Karya-karya seni terap yang lain seperti illustrasi, graffiti atau objek visual lainnya yang semula dikategorikan sebagai seni terap, kini beredar dari satu galeri seni rupa ke galeri seni rupa kontemporer lainnya. Semakin tipisnya batas antara satu displin seni dengan seni lainnya adalah fenomena yang umum terjadi pada dunia seni kontemporer yang dilandasi oleh kebudayaan post modern. Artinya kalau kita memposisikan karya seni kita masih dalam kategori-kategori seni terap dan seni murni, berarti kita memposisikan diri kita dalam masa lalu yang telah ditinggalkan.
Kalau kita masih ingin membedakan antara desain dan seni rupa, maka perbedaan itu terletak pada fungsi. Desain grafis mempunyai fungsi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak, sehingga sebuah desian grafis mengemban fungsi sosial pada pesan yang diemban yang disampaikan kepada khalayak luas dengan melalui media yang sudah direncanakan untuk bisa menjangkau khalayak luas. Sedangkan seni rupa sebagai ekspresi individual yang tak mempunyai fungsi sosial yang bertindak sebagai mediator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas, sehingga juga tidak mengemban tanggungjawab sosial yang sama seperti desain grafis. Namun seni rupa tetap mempunyai tanggungjawab sosial, karena seni rupa juga mempunyai makna dan nilai-nilai sosial. Bagi saya membatasi diri dalam sebuah pengkotak-kotakan justru membatasi cakrawala seorang desainer, seniman atau perupa dalam penggalian ide-ide kreatif dalam proses penciptaan karya seni rupa atau karya desain. Sempitnya orientasi dan cakrawala pada akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai estetis sebuah karya seni sehingga tak akan mampu menembus batasan-batasan seni sebagai bagian dari kebudayaan.
. . .
 FX Harsono
FX Harsono
Perupa & Pendidik
.
![]()
Artikel terkait: Desain itu Seni Terapan – Eka Sofyan Rizal
•••
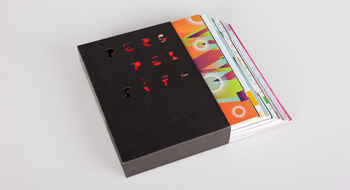



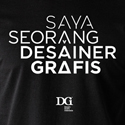



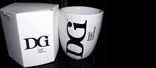

 1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto
1. Nirmana: Elemen-elemen Seni dan Desain | Sadjiman Ebdi Sanyoto 2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong
2. Desain Komunikasi Visual Terpadu | Yongky Safanayong 3. Hurufontipografi | Surianto Rustan
3. Hurufontipografi | Surianto Rustan www.underconsideration.com
www.underconsideration.com

semoga pak Eka Sofyan Rizal bersedia menanggapi artikel ini. amin. hehehehe…
Saya melihat hal itu adalah ‘masalah’ dalam diri puak desainer (grafis) yang rada meng-eksklusif-kan dirinya tanpa sadar. =)
terimakasih pak Harsono atas tanggapan thd artikel sy,
dan atas pencerahan dari artikel ini.
sy sengaja mengangkat pernyataan ‘desain itu seni terapan’ (tepatnya: pertanyaan; krn sy sendiri tdk menganggap pernyataan itu benar absolut, tetapi diumpamakan ‘kalau benar begitu’ seperti dalam pembukaan artikel sy) karena kalimat ini sdh sangat dianggap cliche, sepele dan ketinggalan jaman. padahal kalau mau dicermati, kalimat itu mengandung konsekuensi yg bisa membawa kita memahami perkembangan makna desain dan perbedaan seni dg desain. salah satu konsekuensinya yaitu ttg ‘bersih subyektivitas’.
sy tergoda utk menulis artikel itu krn menyaksikan sendiri banyaknya bukti mahasiswa dan desainer di lingkungan pergaulan sy yg kebablasan membawa prinsip subyektivitas sebagai landasan untuk desain. bersembunyi di balik nama estetika dan seni, mereka melakukan proses yang kurang komprehensif, cenderung langsung menuju sketsa dan ekspresi visual yg kurang membawa kebaruan fungsi ide, hanya bersifat kebaruan tampilan. client brief atau tugas kuliah langsung dijadikan bahan dasar utk membuat solusi tanpa merasa perlu memahami masalahnya secara lbh aktual krn merasa sdh jago atau sudah paham. karya spt ini bisa mencapai kedahsyatan visual, sehingga kita terpana dan tertarik, tetapi setelah ditelusuri ternyata tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, hanya mempergunakan manfaat seni untuk menipudaya. dinamika ini tidak membawa kita ke pemahaman esensial dari desain, malahan makna desain dikerdilkan dengan keterampilan visualisasi saja.
tapi pengkerdilan/pendangkalan makna ini –bahkan menjadikan desain menjadi anti estetik; membentuk suatu yg kitsch (bercita rasa buruk) atau banal (tanpa orisinalitas/biasa)– juga tidak bisa dikategorikan salah; boleh2 saja. toh setiap orang berhak mengklaim (prinsip) dirinya sbg desainer/senirupawan.
‘bersih subyektivitas’ yg sy maksud adalah terbebas dari perasaan personal, cita rasa atau pendapat pribadi (yang tidak berfungsi untuk publik sasaran) sebagai landasan proses desain.
‘bersih subyektivitas’ sy arahkan sbg sub-judul yg tegas; tapi sy tak lupa menitipkan catatan ttg kemungkinan desainer memakai subyektivitas. salah satu cara yg sy rekomendasikan adalah mengambil peran sbg publik yg manusiawi, agar peran desainer dan makna desain tetap tidak kehilangan obyektivitasnya. sebagai bagian dr publik, desainer bisa menitipkan pesan atau mempengaruhi terbentuknya pesan yang tidak hanya berdasar pada kebutuhan pasar yg diinginkan publik, tetapi bisa yang lebih bersifat aspiratif yaitu ide2 utk taraf hidup lbh baik, bahkan yg inspiratif yaitu ide2 baru yg bisa mempengaruhi budaya publik yg lebih beradab.
‘bersih subyektivitas’ juga tidak berlaku pada wilayah kesamaan desain dan seni (misalnya pada konteks pembuatan karya, ekspresi dan visualisasi masalah, yg sdh tentu sangat tergantung dari pengalaman hidup desainernya), karena yg sy bahas adalah upaya untuk menggali perbedaan desain dan seni.
tetapi di lain hal, berpegang pada obyektivitas juga tidak melulu bermakna bahwa itu berteman dg orientasi pasar. desain yg baik, tidak mungkin berorientasi pasar; krn itu cuma akan membuat siklus tak berujung pangkal: desain mengikuti pasar > < pasar mengapresiasi solusi desain. yg diuntungkan dari siklus itu cuma fungsi ekonomi yg menguntungkan utk kalangan dan desainer tertentu. dg begitu, desain yg baik juga sebaiknya jangan berpedoman pada market research, tp memakai hasil riset sbg masukan utk membuat ide pembaharuan.
obyektivitas juga merekomendasikan agar desainernya tidak melulu berada di lingkup desain dan seni saja. dg berpegang pd obyektivitas, desainer diminta utk meluluhkan diri, mengembangkan dan bersinergi dg sektor pengetahuan lain, sehingga justru mengajaknya utk memperluas wawasan dan sudut pandang.
mungkin artikel sy cenderung 'mengkotakkan' desainer utk kembali menggali tanggungjawab fungsi dari karyanya: menyarankan agar jangan terlalu tergoda untuk ingin menampilkan karya impresif, tetapi kmd lupa fungsi karyanya. artikel sy juga cenderung 'mengkotakkan' seni utk bebas sebebasnya memaksimalkan harkat manusia, untuk jangan hanya terpaku pd masa lalu, tapi harus selalu membawa kebaruan di masa kini dan masyarakat.
terimakasih pak Harsono, salam hormat.
Produk2 peralatan dapur misalnya dari merek Alessi pernah dikritisi oleh Viktor Papanek karena melupakan desain sebagai fungsi desain yg bersifat human-centered design dan beralih semata sebagai obyek ‘estetis’ baik itu dengan alasan historis, nilai, maupun ‘branding’.
Barangkali kalau boleh izinkan saya ‘damaikan’ pandangan bahwa mungkinkah seorang desainer memurnikan subyektifitas dirinya dan peranan desainer dalam mengedepankan user-centered design (human-centered design) lewat pandangan Klaus Krippendorf di Semantic Turn: New Foundation for Design:
“…meaning is always someone’s meaning. Human-centeredness must therefore acknowledge that the meanings of interest to designers are embodied in individuals, who, as members of communities, coordinate their understanding by interacting with one another…”
“…We must realize that the understanding of someone else’s understanding of something is….an understanding of understanding….This recursive understanding of understanding is a second-order understanding. Inasmuch as human-centered design is fundamentally design for others, it must be grounded in second-order understanding…”
Desainer bukan saja mampu menghasilkan produk yg berguna bagi klien atau masyarakat (1st order), tetapi juga harus mampu melihat bahwa ia dan klien serta masyarakat adalah agen perubahan adalah agen pengetahuan yang mampu melakukan refleksi atas desain (2nd order).
Saya salut terhadap tanggapan Pak Har dan Eka. Bahwa wacana desain grafis memang masih terjebak dalam dikotomi desain-seni; itu masih ada karena desainer kita tidak didukung untuk berkembang lebih jauh. Saya menduga bahwa paradoks desainer-seniman tumbuh dari sistem pendidikan DKV kita yang kebanyakan eksklusif. Contoh: jurusan DKV merupakan jurusan paling ‘nyeni’ di banyak institusi pendidikan. Pandangan ini dianut oleh mahasiswa DKV-nya sendiri, dan tentu dari luar. Dari pandangan itu saja sudah ada kerancuan bagaimana memandang desain-seni. Kemudian permasalahan ini diperkeruh dengan perkembangan industri yang juga kerdil dari segi infrastruktur. Sehingga ‘desainer’ sebagai profesi harus mati-matian bertahan hidup dengan mencari pekerjaan yang nilainya kian menurun. Mana sempat ia berkegiatan, berwacana, membaca, membuka pikirannya dengan berkunjung ke museum, nonton teater, dan sebagainya. Walau era internet membuka wawasan baru, namun itu menurut saya belum cukup. Ada esens yang tetap hilang dari pengalaman nyata estetik. Kesadaran ‘desain grafis’ sendiri rancu di kalangan desainer grafis Indonesia. Persoalan tugas desainer menjadi topik hangat diskusi di kelas karena mahasiswa yang masuk ke jurusan DKV sendiri sebenarnya tidak ada minat ke sana, tetapi sering terpaksa atau tidak menemukan pilihan atas kemampuannya yang terbatas di bidang lain. Permasalahan pendidikan, industri dan identitas ini membuat cacat perkembangan desainer yang tanpa batas. Mungkin dengan mendobrak batasan itu-seperti Iwang, Erick, Leboye, dsb-justru si desainer bisa membuka lahan pemahaman baru terhadap betapa tipis dan gampang tembusnya kotak itu. Ini catatan penting untuk kita terus diskusikan sehingga bersama mungkin menemukan titik cerah.
membaca artikel kang eka kemudian diteruskan dengna tulisan pak harsono menarik sekali.
saya berpendapat bahwa sebuah karya memiliki nilai “kompromi” dalam permasalahannya, antara subjektifitas dan objektifitas.
Seni Rupa itu ada di dalam Desain.
Terlihat seperti sangat rumit sekali ya… (oh… kreatifitas, seberat itukah bebanmu… aku iba padamu…) yang aku kenal engkau lugu dan bijaksana bahkan menyenangkan… wahai generasi muda teruslah berkarya… Amin.
Saya lebih terkejut lagi melihat tindakan saudara FX Harsono… membuat imajinasi menjadi harus berkutat pada kata-kata…
Apakah commentator dalam dialog ini ada yang mengetahui lebih banyak tentang info-info “pembeli desain graphis yang potensial dengan harga lebih tinggi” yang saya tahu harga dan penghargaan desain di Indonesia sangat menyedihkan dibanding harga dan penghargaan yang dilakukan di negara-negara lain… (mengapa..?).
harga yang tinggi hanya bisa didapat dari klien langganan, dan itu pun dengan banyak bonus kerjaan tambahan.
kenapa kurang dihargai? karena tidak ada ilmunya desain grafis itu. Siapa saja yang sudah belajar software aplikasi desain bisa bikin kartu nama dan menjual dirinya sbg desainer grafis, minimal bikin kartu nama sekotak seharga Rp.30.000,-
Desain grafis itu gratis kalo bikinnya di jasa percetakan atau digital print. =)